Novel serial terbaru karyaku yang diterbitkan Penerbit Kiddo, sejak 9 Maret 2015.
GKNN Buku 1: Dobel Kacau
GKNN Buku 2: Belut Penentuan
GKNN Buku 3: Teka-Teki K2Soul
Book Trailer : Fanmade
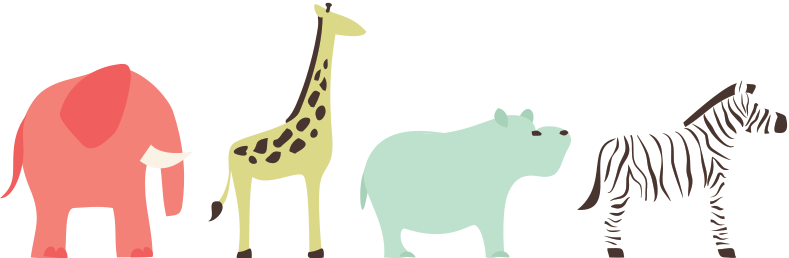

Ada dua ikatan masa lalu yang masih tersisa di kampung halamanku. Aku terpaksa kembali ke sini untuk memutus keduanya agar dapat melanjutkan masa kini. Harusnya tidak terlalu sulit. Aku hanya menumpang lahir dan tumbuh di sini hingga lulus SMP, dan tak ada yang sungguh-sungguh spesial selama itu.
Ikatan pertama adalah ramalan konyol Ina Mara dari pasar malam tahunan di balai desa. Katanya, jodohku adalah cowok yang menabrakku dengan…. Ramalannya tidak selesai karena aku cuma bayar separuh. Hei, aku masih SMP waktu itu, lebih suka jajan bakso ketimbang menerawang jodoh. Beberapa tahun kemudian, aku ditabrak mobil di kampus, dan belakangan, Jodi si penabrak sekaligus penyelamatku itu menyatakan cinta. Aku pernah mencari Ina Mara agar melanjutkan ramalannya. Tapi kata orang, perempuan itu tak pernah datang lagi. Lalu Jodi pergi dengan membawa serta semua warna dari hidupku.Ina Mara can go to hell.
Setahun sesudahnya, aku ditabrak cowok bersepeda. Hasil akhirnya adalah kaki tangan lecet-lecet, pendamping baru selama setengah tahun, plus luka yang terbuka lagi sesudahnya. Kusebutkan nama si Kampret Jamuran itu nanti kalau aku berhasil menemukan Ina Mara dan meminta uangku kembali.
Ikatan kedua adalah rumah peninggalan orangtuaku. Segala kisah di rumah itu sudah masuk peti dan kupendam di dasar memori. Psikologku dulu bilang, aku masih bisa mengaksesnya hanya kalau mau. Dan aku tidak mau. Jadi, sekarang aku berdiri di depan gerbangnya hanya dengan ingatan permukaan. Tapi tak kusangka aku akan tercengang-cengang.
Aku mengharapkan kebun berantakan, tapi sekarang tak bisa lagi disebut berantakan. Jambu, sukun, mangga, sirsak, dan buni, masih ada di tempat aku menanamnya dulu. Sesuai dengan perjanjian dengan caretaker tentu saja, hanya di sekitarnya ditanami rumput dan perdu berbunga membentuk klaster-klaster cantik.Tanaman epifit berbunga menghiasi batang-batang pohon yang kini menjulang. Oke,tampaknya caretaker yang sekarang berusaha mencegah aku menjual rumah ini. Tak akan berhasil. Tekadku sudah bulat. Kalau dia mau tinggal selamanya di rumah ini, ya silakan. Beli saja.
Pintu depan terbuka. Seorang pemuda keluar dan melambaikan tangan. Aku menyeret koper melintasi jalur masuk yang ditanami batu-batu pipih,dan barisan petunia ungu menjuntai di kanan-kirinya. Entah kenapa aku merasa pernah melalui taman seperti ini. Tapi aku tak sempat mengingat-ingat lagi karena pemuda itu sudah menyambutku. Ia mengenakan T-shirt ungu muda, dirangkap kemeja biru polos, celana jeans, tanpa alas kaki.
“Selamat datang,” sapanya, buru-buru membantuku mengangkat koper ke beranda.
“Pak Pandu ada?” tanyaku. Ia hanya memandangku. Berdiri berhadapan, tinggiku hanya sebahunya. Aku mengamati wajahnya. Bersih, seperti baru bercukur. Rambut lurusnya berantakan. Ada yang familiar, tapi aku tidak yakin pernah melihatnya sebelum ini. Dan ia masih memandangiku. Sesaat tampak kecewa. Lalu buru-buru menutupinya dengan senyum lebar. Lesung pipit dan celah pada dua gigi kelincinya langsung mengaktifkan memori tentang sekolah yang ikut terkubur. “Ya ampun. Kamu Ipeng?”
Senyumnya melebar. “Ya. Pangling?”
Aku tertawa. “Jelas. Kamu dulu kecil kerempeng tapi jahil luar biasa. Aku tak pernah melihatmu lagi sejak…. hm…, kamu lulus SD duluan. Berapa lama itu ya?”
“Dua belas tahun, dua bulan, tiga hari.”
Aku mengangkat alis.
Ia mempersilakan aku duduk. Baru kusadari di beranda ada ayunan rotan menggantung dari atap, sebuah sofa nyaman dan rak buku rendah yang berfungsi sebagai meja pula. Aku terkesiap. Kututup mulutku yang nyaris berteriak menyebutkan majalah desain interior yang kusimpan di bawah kasur di rumah ini bertahun-tahun lalu. Jalan masuk dengan barisan petunia, dan beranda ini, ada di majalah itu. Aku menatapnya tajam. Sambil melengos, ia bergumam bahwa aku pasti haus dan ia mau mengambilkan air minum, lalu secepat kilat masuk ke dalam rumah.
Kepalaku mendadak terasa ringan. Aku sudah menahan napas tanpa sadar. Dengan tersengal aku memenuhi dadaku dengan udara. Oke, ini memang aneh. Tapi pasti ada penjelasannya. Mungkin ada di salah satu email dari caretaker pengganti Bu Padmi yang bersubjek tunggal: Rumah di Kampung.
Aku duduk dan memeriksa email di ponsel. Nama caretaker itu E. Pandu Kertapati. Sejak Bu Padmi diboyong anaknya ke Jakarta, rumahku diurus oleh Pak Pandu ini. Entah apanya Bu Padmi. Karena Bu Padmi percaya kepadanya, aku tidak mempermasalahkannya. Bahkan laporan bulanan Pak Pandu seringnya tidak kugubris. Mungkin Ipeng putra Pak Pandu. Mungkin…dan aku tertegun membaca emailnya di awal-awal korespondensi.
Nad,
Jangan panggil aku Pak Pandu dong. Kamu beneran lupa? Aku Ipeng. Kamu dulu memanggilku Elang sebelum kebawa teman-teman lain panggil Ipeng si trouble maker. Salahku juga sih. Suer,aku nyesal suka gangguin kamu. Tahu-tahu kamu pindah jauh. Aku gak sempat minta maaf. Tapi aku senang Bude Padmi percaya aku bisa mengurus rumahmu.
Email berikutnya…
Nad,
Jelas emailku gak selalu kamu baca. Kamu masih panggil aku Pak Pandu, dan hanya membalas email yang ada attachment laporan keuangan dengan ucapan terima kasih.
Dan berikutnya,
Nad,
Sekarang attachment-pun kamu gak buka. Kamu seperti biasa bilang terima kasih. Padahal yang terakhir itu bukan xls, tapi jpg. Gak penasaran?
Dan aku membuka email sebelumnya. Mendownload dua foto. Yang pertama foto ramai-ramai peserta seminar di kampusku. Ada dua wajah dilingkari. Salah satunya aku. Dan ketika kubesarkan gambarnya, satu lagi jelas Ipeng. Aku menelan ludah susah payah. Dengan tangan gemetar kuklik foto kedua, tampak aku dan Jodi duduk berdekatan di kafetaria. Aku menyingkirkan ponsel.
Ipeng atau Elang atau Pak Pandu sudah berdiri di dekatku, menyodorkan segelas jeruk dingin. “Minumlah,” katanya lembut. “Kamu seperti baru melihat hantu.”
Aku tertawa kikuk. “Klise. Bukan hantu. Tapi…. ah sudahlah. Kenapa kamu gak menemui aku di seminar itu? Kenapa gak pernah telepon?”
Ia angkat bahu. “Among the many things I regret.”
Wajahku memanas tanpa bisa dicegah. “Maafkan aku.”
“Hei, tak ada yang perlu dimaafkan. Aku mengerti kamu ingin memutuskan segala kaitan dengan masa lalu, terutama rumah ini.”
Aku mengangguk. “Kamu pasti sudah tahu ceritanya dari Bu Padmi. Aku mengambil risiko dengan datang ke sini.”
Sepi sejenak. Aku menyesap air jeruk. Berterima kasih diam-diam, aku tahu kenapa ia tidak mempersilakan aku masuk. Ia memberiku waktu. Selama ini ia memberiku waktu. Aku mengangkat muka dan mendapati senyumnya. Tidak setampan Jodi, tapi jauh lebih cutedaripada si Gombal Busuk itu. Ah, kenapa tiba-tiba aku membandingkan mereka?
“Kamu masih main skateboard?” tanyanya tiba-tiba.
“Apa? Bagaimana kamu tahu? Aku memulai hobi itu kan di SMA,gak di sini. Tapi sekarang sudah gak lagi.” Dan dalam hati aku melanjutkan, gara-gara si Gagak Brengsek itu yang menganggap sepeda lebih superior ketimbang papan skate. Dan bodohnya aku manut saja.
Elang tiba-tiba bangkit. “Ikut aku.” Ia melompati pagar beranda. Gerakan khas skateboarder. Senyumku mengembang. Aku melompat keluar dengan cara yang sama. Mengikutinya mengitari rumah. Halaman belakang yang dulu juga kebun berantakan sudah disulap menjadi arena skateboard. Ada dua papan skate tergeletak di sana. Aku berjingkrak dan berteriak-teriak seperti anak kecil disemprot air. Elang tergelak.
“Sudah lama aku menyiapkan ini untukmu. Agar kamu tahu, sisa-sisa masa lalu bisa kamu modifikasi menjadi masa kini yang lebih baik.”
Aku terpana. Tapi tanpa menunggu reaksiku lebih lanjut, bertelanjang kaki, Elang menaiki salah satu papan skate dan meluncur berkeliling, dengan gerakan pemanasan mengalir bagaikan menari. Aku menyusulnya dengan papan satu lagi. Tapi kakiku sudah kaku. Sepatu khusus skateboarder yang selalu kupakai pun tidak membantu. Beberapa kali gerakanku tersendat. Dan ketika mencoba melakukan flip sederhana, aku salah mendaratkan kaki, sehingga papanku terpental, tepat memotong jalan Elang yang menuju ke arahku. Elang melompat tangkas, hanya tidak memperhitungkan aku yang bodohnya malah maju untuk menolongnya. Tabrakan pun tak terelakan.
Kami jatuh terjengkang. Saling bertanya apakah terluka. Sesaat kemudian, tawa pun meledak.
“Bagaimana kamu tahu aku suka main skateboard?” tanyaku, mengingat-ingat mungkin pernah membawa papan skate ke tempat seminar. Rasanya tidak.
Elang menyeringai. “Kontes skateboarding di Bandung waktu kita SMA. Aku mendapat petunjuk untuk ikut kontes itu dan melihatmu lagi.”
Aku nyaris kehilangan kata. Tak habis pikir ia hanya melihatku….Hanya! Bagaimana bisa ia diam saja selama ini. “Eh, petunjuk, katamu? Dari siapa?”
Elang tampak gugup. “Oh, ini memalukan.”
“Tell me!” seruku galak.
Elang menggaruk-garuk telinga. “Ina Mara….” Wajahnya memerah. “Dia… ng… di pasar malam…. Ah, kamu gak tahu…sudah lama.”
“Aku kenal Ina Mara. Kamu bayar penuh? Apa ramalannya buat kamu? Apa kaitannya dengan semua ini?”
“Ya, aku bayar penuh. Beberapa kali. Karena aku ingin tahu banyak.” Elang lalu terdiam.
Sikapnya membuatku tegang. Perasaanku mengatakan aku menjadi bagian dari ramalannya. Tapi yang membuat jantungku berkerja keras adalah fakta bahwa dia baru saja menabrakku dengan… tubuhnya. Wangi segar parfumnya masih meliputi udara di sekitar hidungku. Darah panas pun mengalir deras ke sekujur badan, anehnya aku menggigil.
Tapi mendadak Elang bangkit. Ia mengulurkan tangan untuk membantuku berdiri. “Ramalan Ina Mara tak usah dianggap serius. Sebetulnya, gak ada yang percaya. Orang menemui perempuan tua itu cuma karena kasihan dan ingin memberinya uang.”
Setelah berkata begitu, Elang melenggang pergi. Aku merasa ia sengaja menghindari mataku. Menghindari pertanyaanku lebih jauh tentang Ina Mara. Tapi mungkin ramalannya sudah tidak penting lagi sekarang, setelah apa yang terjadi hari ini. Aku menatap pungung tegapnya. Rambut berantakannya tertiup angin senja. Bertanya-tanya, apakah ia bagian dari masa lalu yang harus kulupakan bersama rumah dan ramalan Ina Mara, ataukah….
“Nadine!” Elang berbalik, dan kembali mendekat. Pelan namun tanpa keraguan, ia melanjutkan, “Ina Mara cuma mengajari aku bersabar. Karena aku adalah masa depanmu.” []
[Ary Nilandari, Kuala Lumpur 19 November 2014]

Setujukah kamu, kalau kukatakan Pinky Bunny adalah nama paling konyol untuk seekor anjing? Apalagi untuk anjing sejenis labrador retriever berbulu hitam, seperti aku. Entah kenapa Alicia dan Alana menamaiku seperti itu. Yang aku tahu, sejak aku berusia dua minggu dan dibeli mama mereka dari sebuah petshop, aku sudah dipanggil Pinky oleh Alicia, dan Bunny oleh Alana. Jadilah aku Pinky Bunny, kelinci merah muda.
Tapi itu belum seberapa dibandingkan perlakuan si kembar terhadapku. Mereka biasa mendandaniku seakan aku sebuah boneka atau seekor pudel. Hasilnya, aku lebih buruk dari badut manapun. Sudah menjadi sifat rasku, aku setia, penurut, dan senang bermain dengan anak-anak. Tapi tolong, jangan rok ketat dan blus berumbai. Aku sering terjungkal karenanya.
Labrador retriever itu ras pintar. Aku anjing pintar. Aku bisa mengambilkan sepatu, koran, bahkan telur rebus (kalau diberi kesempatan), tanpa merusaknya dengan gigitanku. Sayang, tampaknya keluarga majikanku tidak percaya itu. Aku tak lebih dari binatang bodoh yang mau diapakan saja asal mendapatkan makanan.
Nah, soal makanan ini lebih mengerikan. Lihat badanku! Kurus sekali. Aku kurang makan. Kadang mereka ingat untuk membelikan aku makanan khusus bergizi. Namun lebih sering, mereka hanya memberiku kue sisa. Dalam hal ini mereka sangat pemurah. Ya, Mama senang sekali membuat kue, dan paling sering membuat brownies. Karena itu aku menyebutnya Mama Brownies. Tapi brownies buatannya tak pernah sukses. Sering bantat atau gosong. Mereka hanya mencicipi sepotong lalu membuang semua sisanya ke mangkuk makananku. Aku yang kelaparan tak punya pilihan lain, bukan?
Dan satu lagi yang membuatku sedih adalah mereka hampir tidak pernah membawaku berjalan-jalan. Aku biasa dikurung di dalam rumah, atau dirantai di halaman. Kalau sudah begini aku merindukan Jenna. Jenna itu sepupu si kembar. Dia tinggal di kota lain. Setiap kali berlibur di sini, Jenna memanjakan aku. Dia memperlakukan aku dengan layak, bahkan mengajakku berjalan-jalan dan berenang. Ya, dia tahu aku jagoan berenang.
Jika Jenna bersiap-siap pulang, aku akan terus menguntitnya. Sudah jelas, aku ingin dibawanya pergi dari sini. Tapi Jenna hanya menepuk kepalaku. “Maaf, aku tidak bisa membawamu. Kamu milik Alicia dan Alana. Dan aku sudah punya Donika,” katanya. Donika itu kucing betina peliharaannya. Pernah Donika dibawanya menginap di sini. Kami berteman baik. Alicia dan Alana menjadi tidak puas. Kata mereka, anjing dan kucing seharusnya bermusuhan. Ah, teori dari mana itu!
Mereka lalu menggerakkan cakar-cakar Donika untuk menggangguku agar aku marah dan mengejar Donika. Ketika aku tidak peduli, mereka mengata-ngataiku anjing bodoh. Aku hanya mendengking pelan. Syukurlah, Donika berhasil melepaskan diri dan lari mencari Jenna.
Begitulah kehidupanku. Mungkin selamanya tidak akan berubah kalau saja tidak ada dua kejadian seru hari ini. Yang pertama, Mama Brownies kehilangan cincin permatanya. Yang kedua, Jenna datang. Mama Brownies percaya Jenna berbakat menjadi detektif. Itu sebabnya Jenna dipanggil untuk membantu menemukan perhiasan berharga itu.
Jenna mengajukan banyak pertanyaan kepada Mama Brownies. Kapan terakhir cincin itu dipakainya? Tadi pagi. Di mana biasanya cincin itu disimpan? Di kotak perhiasaan di kamar. Tapi kotak itu kosong. Kalau sedang bekerja di dapur, Mama Brownies menyimpan cincinnya di dalam cangkir di atas kulkas. Cangkir itu sudah diperiksa, kosong. Apa saja yang telah dilakukan Mama Brownies sejak pagi hingga siang ini? Berbelanja di tukang sayur, memasak lauk pauk, membuat brownies kukus, menelepon untuk memesan gas dan air mineral galon, menemui Ibu RT yang bertamu, dan menyajikan brownies kukus kepadanya. Siapa saja selain keluarga yang telah memasuki dapur? Tukang sayur yang membawakan ikan, dan si Tanto yang membawakan gas dan air galon.
Mama Brownies tiba-tiba menjerit, “Astaga Jenna, apakah cincin Tante dicuri salah satu dari mereka? Tukang sayur atau si Tanto?”
Jenna menggeleng. “Belum tentu, Tante. Kita tidak boleh menuduh sembarangan.”
Aku menyalak. Jenna benar. Tentu saja mereka tidak mengerti maksudku.
Tapi Jenna tersenyum memandangku. “Aku perlu bantuan Labby.”
“Labby?” tanya Mama Brownies dan si kembar terbelalak.
“Oh, aku lebih suka memanggil anjing kalian Labby, singkatan untuk Labrador. Dia sangat pintar, penciumannya super tajam, dia pasti bisa membantuku menyelidiki kasus ini.”
Ketiga majikanku menatapku tak percaya. Mama Brownies angkat bahu. “Silakan saja, Jenna. Yang penting, cincinku bisa ditemukan sebelum Om kamu datang. Cincin itu pemberiannya.”
“Kalau kamu bisa menemukan cincin itu, Pinky boleh kamu bawa pulang,” kata Alicia.
“Ya, aku juga sudah bosan dengan Bunny, yang tidak bisa apa-apa.” Kembarannya menimpali.
Jenna tertawa. “Aku akan senang sekali memelihara Labby. Ya kan, Labs?”
Aku menyalak beberapa kali menyuarakan persetujuan dan kegembiraanku. Ini tantangan bagiku. Aku harus membuktikan diri kalau ingin lepas dari Pinky Bunny untuk menjadi Labby.
Maka setelah mengikuti perintah Jenna untuk mengendus cangkir tempat cincin dan jari manis Mama Brownies, aku mulai melacaknya. Aku hapal bau cincin itu. Bau logam emas campur aroma brownies gosong dan keringat khas Mama Brownies. Dari jari manis Mama Brownies, cincin itu pernah ada di mangkuk adonan.
“Hmm…Labby, apakah kamu mengira seperti yang kukira?” Jenna bersemangat membuka dandang. Loyang brownies kukus masih ada di sana. Kosong. Aku mengendusnya. Ya, ada bau samar cincin itu di sini. Tapi benda itu sudah dibawa ke tempat lain.
Aku berkeliling dapur mencari-cari dan menemukan jejaknya menuju ruang tamu. Bau cincin itu menguat di atas meja. Di sebuah piring kue. Tapi tak ada apa-apa di atas piring.
“Itu piring kue bekas Bu RT. Oh, dia kuberi sepotong besar brownies dan semua habis disantapnya. Tapi apakah dia yang….” Mama Brownies tidak meneruskan kalimatnya. “Dasar anjing tidak punya otak, mana mungkin Bu RT mengambil cincinku.”
Aku tidak memedulikan celaannya. Kuendus tempat tisu. Cincin itu pernah di bawa ke sini. Jenna membantuku mengeluarkan tisu sampai kotaknya kosong. Tidak ada apa-apa. Aku semakin bersemangat. Mengendus udara ke arah jendela.
“Ayo Labby, aku tahu kamu semakin dekat.” Jenna menepuk kepalaku.
Aku melompat keluar dari jendela, dan membaui udara di halaman. Jenna menyusulku. Si kembar juga.
“Pasti tukang sayur,” tebak Alicia.
“Tidak. Menurutku, lebih mungkin pelakunya si Tanto,” bantah Alana.
“Tidak dua-duanya,” kata Jenna senang. “Lihat, Labby sudah menemukan cincin mama kalian!”
Aku menyalak. Di dekat tong sampah, ada gumpalan tisu berisi brownies kukus bantat yang tidak enak. Bu RT melemparkannya ke sini melalui jendela dari ruang tamu ketika Mama Brownies tidak melihatnya.
Jenna menggunakan ranting untuk meremukkan brownies keras itu. Dan muncullah di tengah kepingan-kepingan cokelat itu sebentuk cincin emas permata.
Si kembar melonjak-lonjak memanggil mama mereka dan memuji-muji Jenna.
Jenna dengan rendah hati menunjukku. “Labby yang menemukannya, Tante.”
Oh, betapa aku mencintai anak cantik ini. Aku menyalak dan mengangkat kaki depanku.
Jenna tertawa. “Tante, Labby mungkin mau menjelaskan, cincin ini lolos dari jari Tante sewaktu Tante membuat adonan. Lalu ikut terkukus di dalam brownies. “
Tante memeluk Jenna dengan bahagia. “Terima kasih Jenna. Terima kasih Labby. Kalian pasangan detektif yang hebat.”
Itu pengakuan luar biasa. Artinya, sejak saat itu aku resmi menjadi milik Jenna. Senangnya… Tak ada lagi si Pinky Bunny dengan rok berenda dan topi kerucut. []
(Cerpen favorit lomba cerpen misteri Bobo 2009 dan diterbitkan di buku kumcer Bobo)

Enver adalah anak lelaki biasa berumur 10 tahun. Seperti anak lelaki kebanyakan, dia bersekolah, berteman, suka main bola dan membaca; yang paling disukainya adalah buku detektif. Enver juga bisa merasa gembira, sedih, takut, atau marah. Hanya satu hal yang membuatnya berbeda: kakeknya adalah tabib di Negeri Lima!
Enver adalah cucu ke-5 dari putra ke-5, yang lahir pukul 5 pagi, tanggal 5 bulan 5. Dan itu artinya, Enver adalah calon tabib yang akan menggantikan Kakek menjadi tokoh terpenting di Negeri Lima. Tapi itu kelak. Sementara ini, Enver menjalani kehidupan normal seperti kamu.
Hanya jam kakek yang selalu mengingatkan Enver pada Kakek dan negerinya. Enver geli dengan istilah jam kakek itu. Dalam bahasa Inggris, jam berpendulum di dalam kabinet kayu disebut grandfather clock, jam kakek. Tapi jam kuno tinggi besar di ruang duduk ini memang milik Kakek. Jam itu berdentang dua kali saja setahun. Yaitu pada pukul 5 pagi dan 5 sore, tanggal 5 bulan 5. Saat itulah jam kakek akan menjadi pintu keluar masuk Negeri Lima. Kakek pun akan datang pukul 5 pagi untuk mengunjunginya. Lalu sorenya, pada dentang terakhir pukul 5, dia menghilang kembali di dalam jam.
Hari ini, Enver berulang tahun ke-10. Dia sedang menghitung detik-detik menjelang pukul 5 tepat. Ding dong ding dong…BLAK!! Pintu kabinet jam membuka keras. Seorang lelaki terhuyung keluar.
“Kakek!” seru Enver gembira. “Ayah, Ibu! Kakek datang!”
Lelaki itu tinggi tegap berambut hitam pendek. Itu bukan Kakek. Kakek sudah agak bungkuk dan rambutnya kelabu. Enver membeku di tempat.
“Hai, kamu pasti Enver. Aku Primo, kakak tertua ayahmu.” Suaranya berat menyenangkan. Ayah maju memeluknya penuh kerinduan. Enver menjadi lega. Tapi segera muncul kecemasan. Baru sekali ini Kakek melewatkan kunjungan setahun sekali. Mungkinkah ada masalah sangat serius?
Benar. Ternyata Kakek terserang penyakit lupa, lalu tak sadarkan diri beberapa hari ini. Segala upaya untuk menyembuhkannya tidak berhasil. Masalah kedua adalah, di luar istana terjadi antrean rakyat yang menderita. Tampaknya Kakek telah mencobakan semacam obat kuat pada mereka, karena rakyat menginginkan tenaga berlipat ganda untuk bekerja. Tapi akibat kepikunan mendadak itu, Kakek salah meramu obat. Timbullah penyakit aneh-aneh: tumbuh ekor atau tanduk di badan, hilang mulut atau sebelah telinga, rambut sekaku ranting, suara berubah jadi kicauan, dan sebagainya.
Kakek juga tidak mampu membuat ramuan pembalik keadaan. Dan di Negeri Lima, tak ada tabib lain. Artinya tabib pengganti sudah harus bertugas. Enver harus dibawa ke Negeri Lima untuk mengatasi keadaan gawat itu.
“Tapi Kak,” kata Ayah. “untuk menjadi tabib , Enver harus belajar dulu bertahun-tahun.”
Primo mengangguk. Biasanya memang begitu, tapi untuk Enver, Kakek yakin bakatnya bisa muncul kapan saja. Itu sebabnya, Kakek mewasiatkan sebuah surat untuk dibaca Enver dalam keadaan darurat. Dan sekaranglah saatnya.
Ayah dan Ibu akhirnya mengizinkan Enver pergi ke Negeri Lima. Primo berjanji akan membawa pulang Enver tahun depan. Enver tidak berkeberatan, ini demi Kakek dan negerinya.
Sorenya, tepat dentang terakhir pukul 5, Enver menghilang di dalam jam kakek bersama Primo. Enver diminta membayangkan hal-hal menyenangkan agar perjalanan melintas terasa singkat. Enver mengenang kunjungan Kakek dua tahun lalu. Ibu membuatkan es delima kesukaan mereka berdua. Sirup merah kental itu sedang disesap Kakek, ketika Enver tanpa sengaja menyenggol tangan Kakek. Es delima puntumpah membasahi jubah Kakek.
Ibu berusaha membersihkan jubah itu sebelum pukul 5 sore. Tapi akhirnya, Kakek pulang dengan jubah masih bernoda merah basah. Enver mengucapkan sesuatu yang membuat Kakek tergelak. Apa ya yang diucapkannya waktu itu?
Tiba-tiba terdengar Primo berkata, “Buka matamu, kita sudah sampai.”
Enver melihat Kakek terbaring dengan mata terpejam. Beberapa orang dewasa dan anak-anak mengerumuni ranjangnya.
“Mereka semua kerabatmu. Nanti saja kenalannya. Sekarang, terimalah wasiatmu ini.” Primo memberinya sebuah amplop.
Enver memandang ke luar jendela. Halaman istana penuh orang yang mulai tidak sabar. Prajurit mencoba menahan mereka. Ya, waktunya tidak banyak. Dibacanya surat Kakek yang ditujukan khusus untuknya:
Biru dalam kanvas. Sesuatu yang memadamkan api. Kaubuat pulau SD 5.
Enver membacanya berulang-ulang. Apa artinya ini? Adakah kasus seperti ini dalam buku-buku detektif yang pernah dibacanya? Mungkinkah pesan ini semacam kode rahasia yang mengungkapkan sesuatu? Dia gugup. Semua mata di ruangan itu seperti menatapnya, termasuk makhluk-makhluk di dalam lukisan. Lukisan? Biru dalam kanvas. Kanvas… Aha! Lukisan!
Enver mengamati sekelilingnya. Banyak lukisan di dinding. Dan matanya langsung menangkap tiga lukisan yang dikuasai warna biru. Lukisan laut dan pulau es, lukisan rumah bercat biru, dan lukisan potret Kakek berjubah biru. Enver meminta tiga lukisan itu diturunkan. Dia merasa lebih percaya diri sekarang. Dia sudah menemukan biru dalam kanvas.
Sekarang, sesuatu yang memadamkan api. Air laut dan es, bisa memadamkan api. Rumah bisa terbakar, jadi lukisan itu disingkirkannya. Bagaimana dengan jubah biru Kakek? Bisa terbakar, pikirnya, tapi bisa juga memadamkan api kalau jubah itu basah. Ah… ini sulit. Mungkin petunjuk ketiga bisa membantunya. Kaubuat pulau SD 5.
Ada pulau di lukisan laut. Enver meminta kaca pembesar. Dengan alat itu dia mencari-cari di pulau es. Ya, ada bangunan kecil seperti sebuah sekolah di sana. Dan ya, ada tulisan kecil, SD 5. Enver nyaris bersorak. Tapi naluri detektif menahannya. Ini terlalu mudah. Siapa pun di ruangan ini bisa menemukan pulau SD 5. Padahal seharusnya hanya dia yang bisa.
Kenapa harus dia? Hanya dia? Berarti dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Kaubuat pulau SD 5.
Enver tercenung. Dia membuat pulau SD 5, bukan menemukannya. Pulau SD lima. Pulau S Dlima… Pulau es delima…. Ya ampun. Enver terlonjak. Itulah yang coba diingatnya tadi.
Ketika jubah Kakek tersiram es delima, noda terbentuk seperti pulau merah di atas lautan biru. Enver menyebutnya pulau es delima di jubah Kakek. Dan Kakek sambil tertawa mengatakan, jubah ajaibnya menyerap apa saja, tidak akan pernah kering, kecuali kalau digunakan untuk memadamkan api.
Itu dia. Enver menoleh pada orang-orang di ruangan, “Mana jubah biru Kakek?”
Salah satu wanita beranjak ke lemari besar. Di dalam lemari itu tampak sederet jubah biru. Enver dengan mudah menemukan jubah berpulau es delima di antaranya. Lalu, apa maksud Kakek dengan jubah biru ini? Enver memeriksa semua sakunya. Tak ada apa-apa. Primo membantunya. Mereka nyaris berputus asa karena jubah itu tampaknya hanya jubah bernoda merah basah. Tidak ada apa-apa.
Enver mengembuskan napas. Tenang. Ini Negeri Lima. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di sini. Pelan-pelan dia menggumamkan wasiat Kakek, untuk memeriksa apakah ada petunjuk yang terlewatkan olehnya. Biru dalam kanvas. Sesuatu yang memadamkan api. Kubuat pulau es delima.
PUFF!
Jubah itu berubah menjadi botol kecil berisi cairan biru di tangan Enver. Enver terpukau. Wasiat itu merupakan mantra juga untuknya!
Semua bersorak. Primo berkata, “Kamu berhasil, Enver. Itu ramuan pemulih yang sangat langka. Dibuat dari setetes liur elang biru yang muncul sekali saja dalam seabad.Tidak boleh jatuh ke tangan jahat. Makanya disembunyikan kakekmu. Tapi tak kusangka, ramuan itu sedikit sekali. Tidak akan cukup untuk semua orang di luar sana. Bagaimana ini?”
Enver tersenyum. Ramuan itu bukan untuk rakyat, tapi untuk Kakek. Setelah meminumnya, Kakek pun terjaga. Kesehatan dan ingatannya pulih. Segera dia membuat ramuan pembalik keadaan bagi rakyat. Enver menjadi asistennya.
“Kek, apa yang terjadi kalau aku gagal memecahkan teka-tekimu?” Enver penasaran.
“Oh, paling kamu menjadi kodok!” Kakek tergelak dan mengedipkan mata.
Enver meringis. Kakek bercanda, pikirnya. Tapi tiba-tiba didengarnya dengkungan kodok di luar. Kaki Enver berjengit. Tekadnya pun menguat: dia akan belajar keras dalam setahun ini sebelum pulang kepada ayah-ibunya. Kelak… ya kelak, dia akan menggantikan Kakek. Tapi kelak itu masih lama sekali. []
Ada sebuah negeri di kaki pelangi. Sekilas pandang saja, keadaannya membuat hati trenyuh. Sepi, murung, dan lesu, bahkan di pasar dan sekolah. Kenapa? Menurut buku sejarah negeri itu, seabad lalu, terjadi duel antara rajanya dan penyihir hitam. Raja menang. Tapi penyihir hitam yang licik sempat melancarkan kutukan sebelum menghilang. “Vocalittera!! Huruf hidup akan mendatangkan bencana bagi kalian.”
Kutukannya terdengar sepele. Tapi penduduk segera tahu, hidup mereka selamanya tak akan mudah lagi. Sejak saat itu, bayi-bayi diberi nama dengan rangkaian huruf mati yang sulit diucapkan. Seperti Krn, Nd, dan Snt. Toko-toko menghapus huruf hidup pada papan nama mereka. Jadi, TK BRG bisa berarti toko burung atau toko barang. Orang yang ingin membeli roti bisa keliru masuk ke toko Rita yang menjual perhiasan.
Huruf hidup juga harus dibuang dari percakapan. Tak heran penduduk memilih tidak berbicara. Untuk berkomunikasi digunakan bahasa isyarat atau pesan tertulis di kertas. Misalnya, “B, Nyl prg k rmh tmn. Plng sr.” Bisa kau tebak artinya? Yah, sangat merepotkan. Walaupun penduduk akhirnya terbiasa dengan rangkaian huruf mati.
Kutukan itu bukannya tak pernah terbukti. Di masa lalu, banyak penduduk yang tidak percaya. Mereka menantang, “Kutukan konyol! Kami tak takut menggunakan huruf hidup. Dengarlah, A I U E O!”
Seketika kilat membelah langit tanpa diikuti halilintar. Mereka menjadi batu. Bongkahan batu itu masih tegak di alun-alun, menjadi peringatan mengerikan bagi seluruh negeri.
Raja sekarang menjanjikan hadiah bagi orang yang bisa memunahkan kutukan. Sudah lama pengumuman itu dipajang di mana-mana. Belum ada yang menanggapi. Orang bilang, karena huruf matinya sulit dibaca. Padahal sudah jelas, tak ada yang tahu bagaimana mengakhiri kutukan itu. Penyihir hitam pasti sudah lama tiada, rahasianya pun ikut terkubur. Tak ada harapan.
Benarkah? Selalu ada harapan, pikir Thn. Anak laki-laki itu satu-satunya orang yang senang mengunjungi perpustakaan. Tentu saja buku-buku lama yang mengandung huruf hidup sudah dimusnahkan, diganti koleksi baru berisi huruf mati saja. Tapi Thn membaca semuanya, terutama buku sejarah tentang raja-raja lama dan penyihir hitam. Thn menemukan catatan bahwa penyihir hitam memiliki lima anak buah. Anubis bermata tujuh, Eagre makhluk berbentuk gelombang laut raksasa, Ikthyornis burung bergigi pembenci sinar matahari, Ocelot kucing liar penyembur api, dan Unicorn air.
Thn segera menyadari kunci kutukan vocalittera ada pada kelima makhluk itu. Nama mereka adalah petunjuknya. Menurut buku, makhluk-makhluk itu bisa hidup ribuan tahun. Dia harus mencari mereka. Terlebih dulu, dia menemui raja untuk mengisyaratkan temuannya. Mata raja berbinar dengan harapan. Diberinya Thn seuntai kalung emas yang terbuat dari rangkaian huruf mati. Raja mengisyaratkan bahwa kalung itu bermuatan sihir dan mengajarkan penggunaannya.
Thn memulai perjalanannya. Jatuh bangun mendaki tebing utara yang terjal. Hanya tekad dan semangat yang membawanya ke puncak. Seperti tertulis dalam buku, Anubis bisa ditemukannya di salah satu gua. Tampak huruf A di dadanya. Itu dia, pikir Thn. Dia menunggu Anubis pulas untuk mengambil huruf itu. Tapi dengan tujuh mata, Anubis tak pernah bisa pulas. Dia bahkan menemukan Thn yang bersembunyi.
“HAA! Aku tahu apa yang kaucari,” teriaknya. “Penyihir sudah mati. Aku tak perlu menjaga A ini lagi. Akan kuberikan padamu kalau bisa membuatku pulas. Aku penat sekali, tidak pernah tidur sungguhan selama ratusan tahun.”
Thn mendekati Anubis dan memberinya Z dari rangkaian kalungnya. Begitu A digantikan Z, Anubis mendesah, “ZZZZZZ.” Dan tertidurlah semua matanya dengan nyenyak.
“Nah!” Thn tertawa. “A sdah kdapatkan. Skarang k lat!” Dengan A di tangan, Thn bisa merangkai kata camar raksasa dengan huruf-huruf sihirnya. Binatang itu menerbangkannya ke laut selatan.
Di laut, tampak Eagre menghantam pantai dengan gelombang raksasanya.
“Apa yang ka lakkan?” tanya Thn tanpa takut.
Eagre menatapnya dengan frustrasi. “Lihat buah-buahan ranum itu. Bagaimana aku meraihnya tanpa menumbangkan pohonnya?”
Thn melepaskan beberapa H dari kalungnya. Menyusunnya ke atas dan menyandarkannya pada pohon. Dengan segera susunan H itu berubah menjadi tangga. Dia naik dan memetik beberapa buah untuk Eagre. Makhluk yang gembira itu memberikan E kepadanya.
“Terma kash,” kata Thn. Senang kata-katanya mulai hidup. Tapi masih ada burung pembenci terang yang harus ditemuinya. Ikthyornis tinggal di tengah hutan lebat, di kedalaman sebuah lubang.
“Aku tahu kau mencari I. Cari saja sendiri di dasar lubang. Aku menjatuhkannya entah di mana,” kata makhluk itu.
Thn merangkai kata cahaya dengan huruf-huruf sihir yang dimilikinya. Seberkas sinar menerangi dasar lubang. Burung bergigi itu menutup mata dan mengepakkan sayap dengan garang. “Pergi!” serunya memamerkan taring runcing.
Untunglah Thn menemukan I segera di salah satu sudut. Dia keluar sebelum makhluk itu mengamuk. “Kini ke kawah!” katanya kepada camar.
Ocelot mendekam di dalam kawah. Huruf O sihir melingkari lehernya. “Aku kepanasan dan haus,” katanya. WHUFF! Api menyembur ketika dia berbicara.
“Kasihan,” kata Thn. Diambilnya S dari kalungnya. Dilemparkannya ke kawah. Terdengar desisan sssssss. Api padam dan kawah kini tertutup es. “Asyik!” sorak Ocelot. Apinya mencairkan sebagian es. “Aku bisa minum dan main seluncuran sepuasnya! Ini, ambilah O-ku. Aku lelah menjaganya.”
“Tinggal sat lagi,” kata Thn. “Tapi di manakah nicorn tinggal? Tak ada informasi tentangnya, kecali bahwa ia ada di dalam air.”
Thn membentuk kata teropong. Dengan alat ajaib itu dia menyapu sekeliling lereng gunung. Ditemukannya sebuah danau di kejauhan. Teropongnya menembus kedalamannya. Ya, tampak Unicorn di dasarnya. Segera Thn menaiki camar menuju ke sana.
Di pinggir danau, Thn mengikatkan magnet di ujung tali. Dilemparkannya bentukan huruf sihir itu ke air. Beberapa saat kemudian, talinya bergerak-gerak. Dia berkutat menariknya. Magnet telah menempel kuat pada tapal kaki Unicorn. Makhluk itu terpaksa melepaskan U dari sepatunya agar bisa terlepas dari jeratan magnet.
Thn berhasil mendapatkan huruf hidup terakhir. Dengan senyum lebar dia berkata, “Aku Thn. Sudah kubebaskan negeriku dari kutukan. Tugasku selesai.”
Belum. Thn lupa. Dia belum menggunakan huruf-huruf temuannya untuk menghidupkan namanya sendiri. Kira-kira apa ya nama yang cocok untuknya? []
(Dimuat di Majalah My Story- Chil Press, Edisi Perdana, November 2008)
Part 1
Kiran: My Misery and Mystery
Kenapa aku harus jadi seniman? Apa hanya karena aku keturunan seniman? Papiku pemahat ulung. Mamiku master pematung. Omku pelukis kondang pendiri Griya Seni yang jadi ikon high class dan prestige. Tanteku pengubah barang bekas jadi benda seni berharga jutaan rupiah. Itu baru di generasi mereka, yang tinggal empat orang itu. Belum lagi kalau dirunut ke belakang sampai para leluhurku. Pokoknya selalu ada seniman, lebih dari satu, dalam setiap generasi.
Tapi di generasiku… oh sialnya! Cuma aku! Om-tanteku nggak akan pernah punya anak. Papi-Mamiku terlalu sibuk untuk memberi aku adik. So, I am the center of their world! Dan mereka berebut menentukan masa depanku. Kiran, kalau besar kamu mau jadi seniman apa?
Bayi lain pasti disodori jari bunda atau kerincingan waktu baru bisa menggenggam. Aku, pensil dan krayon! Besar dikit, kuas dan cat! Lalu, tanah liat. Terus seabreg barang bekas. Bedtime story-ku seringnya tentang warna, bentuk, pencahayaan, perspektif. Lalu ketika aku mulai jatuh cinta pada Teenage Mutant Ninja Turtles, mereka menjejaliku dengan kisah-kisah the true Leonardo da Vinci, Raphael, Michaelangelo, dan Donatello. Akibatnya, kura-kura ninja itu sering muncul dalam mimpi burukku, bukan membawa katana, sai, nunchaku, dan bo, tapi kuas, pahat, palu, dan cat. Oh help me, God!
Ada bukti dari foto-foto. Bahkan di usia tiga tahun aku sudah menunjukkan bakat besar untuk jadi pemberontak! Aku mematahkan pensil dan krayon, membakar kuas dan kanvas, membuang cat ke selokan, dan meluluhlantakkan barang-barang bekas dengan palu. Apa kata mereka?
“Kiran sedang berekplorasi!”
“Dia akan menciptakan seni cabang baru!”
“Untuk kreatif, kadang perlu destruktif dulu!”
AAAKKH! Jeritanku mengguncang dunia. Sayangnya hanya duniaku. Dunia mereka sama sekali tak tersentuh.
As if it was not big enough misery for me, di depan kelas sekarang berdiri omku, menggantikan Bu Sofie, guru seni rupa yang cuti melahirkan. Kok ya dia! Kayak planet bumi sudah kehabisan guru pengganti saja!
“Kita beruntung. Seorang seniman kaliber dunia menyempatkan diri mengajar di sini untuk membantu menggali bakat kalian! Anak-anak, inilah Pak Giri Dananjaya!” Kepsek mengakhiri pidatonya dengan tepuk tangan keras. Kelas pun menyambut meriah, lengkap dengan standing ovation segala. Om Giri menebarkan senyum, dan berhenti ketika menemukanku. Matanya berbinar. Gotcha! You cannot run anymore!
Bahuku diguncang Jaka. “Ran! Om Giri pasti bisa bikin gue jagoan melukis cewek kayak lo!”
Ingin sekali aku bisa membanting bom asap dan menghilang. Ketahuan deh. Ya, kuakui aku berbakat melukis. Horor awalnya, tapi akhirnya kujadikan modal cari perhatian cewek-cewek. Mereka berdatangan ingin kulukis dan buntutnya dating. Kecuali satu cewek, murid baru itu. Bukan cuma dia alergi dilukis, tapi juga alergi padaku. Baginya, I simply do not exist. Alasannya masih misteri. Misteri yang membuatku rajin ke sekolah untuk mengadakan pendekatan. Tapi sejauh ini, nol besar.
Tugas pertama dari Om Giri disambut lebih meriah. Dia akan membawa kami berkunjung ke Griya Seni sekarang juga. Bus sudah disediakan olehnya. Aku merosot lesu di bangku. Tak bisa menghindar lagi. Setelah peresmiannya 10 tahun lalu, gedung itu menjadi tempat yang kutandai dengan X besar di peta otakku, bersama bengkel Papi, workshop Mami, dan garasi Tante Lian.
Masuk bus paling akhir, aku sempat menembakkan pandangan sebal kepadanya. “Good try! Tapi jangan harap, Om.”
Om Giri menyeringai. “Kita lihat saja nanti, jagoan!”
Di Griya Seni, aku memisahkan diri. Teman-teman membuntuti Om Giri, dari satu lukisan ke lukisan lain, dari satu karya seni ke karya seni lain. Om Giri pasti lagi berceloteh bahwa karya seni tidak boleh dipajang sembarangan. Karya seni tertentu membutuhkan bentuk ruangan dan pencahayaan tertentu, bla bla bla. Jadi, bisa saja satu ruangan hanya dihuni satu karya. Dan di sini, yang dipajang hanyalah masterpiece, karya Om Giri sendiri atau karya seniman lain, bla bla bla. Om Giri juga punya koleksi lukisan kuno. Yang tertua adalah dari awal abad ke-18.
Aku ada di ruang lukisan tertua itu. Sendirian. Pertama (dan terakhir) kali aku kemari, lukisan itu belum ada. Om Giri bilang, lukisan itu sumbangan seorang kenalan di Belanda. Menurut kenalannya itu, lukisan itu sudah lama ingin pulang ke negeri asalnya. Gaya bercanda seniman memang aneh, pikirku.
Berdiri tepat di depan rantai pembatas, memandang lukisan itu, aku terkesima. Tiba-tiba saja aku merasa telah berada di dunia lain. Dan di hadapanku berdiri seorang wanita, tapi dia memalingkan muka. Yang kulihat hanyalah rambut panjang tergerai menutup sisi wajahnya hingga ke dada. Beberapa saat aku terpaku, menunggu wanita itu memutar kepalanya dan menghadapku. Aku ingin sekali melihat wajahnya. Ingin sekali. Sampai kapan pun akan kutunggu….
“Dia nggak akan menunjukkan wajahnya!” kata suara ketus di belakangku.
Aku menoleh kaget. Murid baru itu, yang bagi kelas 11A bukan baru lagi, karena sudah tiga bulan dia bergabung. Dia di sini mengajakku berbicara? Mimpikah aku? Ahh, dadaku mengembang. Mendadak ringan, melambung. Apa nama perasaan ini? Sudah adakah di kamus? Aku ingin terus begini, tapi matanya begitu menusuk.
Earth to Kiran! Earth to Kiran! Go back now! Aku menarik napas berat dan kembali menapak bumi.
“Oh. H-hai Tya!”
“Aku bete keliling. Aku kuntit kamu sampai sini. Keberatan?”
Aku menggeleng cepat dan kuat-kuat. Biarpun nada bicaranya selalu galak kepadaku, seratus persen aku rela. Lalu ada jeda. Dia mendekati lukisan. Aku semakin kikuk.
“Mana Rista?” tanyaku dan langsung menyesal. Bodohnya! Tentu saja dia ikut rombongan. Rista, sahabatku yang kebetulan jadi teman sebangkunya, sering kujadikan alasan untuk mendekati Ayutya. Baru kusadari menanyakan Rista sudah jadi kebiasaan buruk.
Dia hanya angkat bahu dan terus mengamati wanita dalam lukisan. “Kamu tahu kisahnya?”
Aku menggeleng. Om Giri tak bercerita banyak. Atau aku saja yang tak mau mendengarkan.
“Dia Ayundara, ratu sebuah kerajaan kecil di Jawa Barat awal abad ke-18. Seniman desa berbakat bernama Kartaran yang melukisnya. Awalnya, wajah Ayundara menghadap ke depan….”
“Maksudmu, objek dalam lukisan ini bisa memalingkan wajah?” Aku tertawa geli.
Ayutya membungkamku dengan tatapan tajamnya, lalu melanjutkan, “Ayundara jatuh cinta pada Kartaran. Tapi pemuda itu baru menikah dan sangat mencintai istrinya. Dia menolak sang Ratu, sekeras apa pun usaha Ayundara menggodanya. Lalu, ketika lukisannya selesai, Kartaran lari bersama istrinya. Ayundara murka, mengutuk Kartaran dan seluruh pewarisnya.”
Aku meneguk ludah. Kembali memandang lukisan. “Kenapa memalingkan muka?”
“Karena dia malu.”
“Malu?”
“Malu dengan kutukannya sendiri. Bukan hanya keturunan Kartaran yang sengsara, pewarisnya sendiri pun menderita karenanya.”
“Wow! Apa sih kutukannya itu?”
“Semua lelaki pewaris Kartaran akan dibuat menderita oleh para wanita pewaris Ayundara.”
Aku bersiul. “Legenda yang hebat! Kamu tahu dari mana?”
Ayutya mengabaikan pertanyaanku. “Sejauh ini kutukannya sudah menghancurkan enam pewaris di kedua pihak.”
“Ya ampun. Maksudmu, legenda itu nyata?”
Ayutya berkacak pinggang menghadapku. “Kamu ini bodoh atau apa? Kamu pikir aku ke sini cuma buat mendongeng? Cari perhatian? Kamu pikir aku sama dengan cewek-cewek ganjen yang kamu lukis? Sialan kamu! Dasar bego! Aku sudah berharap kamu bukan pewaris itu. Nyatanya, kamu selalu bikin aku sebal sampai ubun-ubun!”
Belum sempat aku mencerna kata-katanya, dia sudah berlari keluar.
“Tya!” Aku ingin mengejarnya, menangkap tangannya, menenangkannya….
Ada yang menahan langkahku. Aku berbalik dan kembali menatap lukisan. Menunggu Ayundara berpaling. Waktu seakan terhenti.
“Kiran!” Suara renyah Rista menarikku kembali. “Ya ampun, kucari kamu ke mana-mana, rupanya bengong di situ. Bus sudah balik ke sekolah, tahu?! Kita terpaksa jalan kaki. Untung nggak terlalu jauh. Tapi pasti kita telat masuk kelas Bu Eva.”
Om Giri membiarkan aku ketinggalan bus?
“Aku yang minta mereka balik duluan. Kubilang, mungkin kamu sedang cari inspirasi. Om Giri kelihatannya senang banget. So, here we are.…” Seperti biasa Rista seakan bisa membaca pikiranku. Tak usah ditanya kenapa dia memilih menemani aku. Setia dalam suka duka, janji yang terus dipegangnya sejak kami masih di TK.
Kami keluar dari Griya Seni, masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Aku dengan legenda Ayundara dan ledakan Ayutya tadi. Rista dengan ponselnya.
“Kiran, seminggu ini aku mempertimbangkan sms-mu.”
“Sms?” Rumah Rista persis di samping rumahku. Jendela kamarnya berseberangan dengan jendela kamarku. Aku tinggal teriak kalau perlu. Untuk apa buang pulsa?
Wajahnya bersemu merah. Aku tercengang. Dia menyodorkan ponselnya. Terbaca:
Ris, aku bosan sahabatan sama kamu. Kita coba pacaran yuk.
Pengirimnya: Kiran Dananjaya.
Langkahku terhenti seketika. Shock. Aku tidak pernah mengirim sms seperti itu. Buru-buru kuperiksa ponselku. Shock lagi. Pesan yang sama ada di folder sent.
“Ris, aku….” Kutelan lagi kalimat yang nyaris terucap. Ekspresi wajah Rista membuatku yakin bahwa mengingkari hanya akan melukai hatinya. Sebelum jelas apa yang terjadi, aku harus hati-hati. Rista sahabatku yang paling berharga. Aku tak mau kehilangan dia gara-gara kejahilan seseorang.
“Aku mau mencoba….” Suara Rista lamat-lamat.
“Trims,” sahutku lebih pelan lagi. Oh, my! Oh my! Benar-benar hari yang bagus untuk mendapatkan banyak masalah sekaligus.
****
Part 2
Ayutya: Pewaris Ketujuh
Aku selalu jatuh cinta pada cowok yang namanya diawali huruf K. K itu eksotis. K itu identik dengan Keren. Keito, Keane, Kavana, Keanu, dan K lainnya. Yap, so far cuma seleb sih. Sampai tiga bulan lalu, di sekolah yang baru….
Meet Kiran Dananjaya!
Tampangnya mirip Kavana. Tapi Kiran lebih oke karena masih muda, imut, dan real! Didukung perawakan pebasket dan otak encer, kurang apa lagi?
Di sekolah, dia satu-satunya cowok K. Dan aku sekelas dengannya, bahkan sebangku dengan tetangga a.k.a. sobatnya, Rista, tambang informasi yang mau memuntahkan muatannya begitu saja. Tapi ceritanya membuat keningku berkerut. Kiran itu smart, easy going, empatik, populer, disayang teman dan guru, dst. Lama-lama aku eneg mendengarnya.
Lalu, kuterima amplop itu.
“A friendship gesture dari Kiran!” kata Rista.
Isinya sketsa pensil wajahku. Tersenyum manis. Lengkap dengan tahi lalat kecil di ujung kiri bibir. Di bawahnya tertulis, “Welcome to 11A!”
Wajahku panas. “Kapan dia…?”
“Seniman tulen. Nggak perlu model diam untuk menangkap karakternya, dan menuangkannya di media apa pun,” celoteh Rista.
Tiba-tiba, sebuah gunung berapi tumbuh cepat di dalam diriku. Magmanya mendesak keluar. “Kapan dia minta izin menggambar aku?” semburku. Tanpa menunggu reaksi Rista, aku mendatangi Kiran. Dia dengan beberapa teman sedang asyik membicarakan film-film baru.
“Hai, Tya. Mau gabung?” tanyanya riang. Anggita dan Raka beringsut, memberiku tempat di samping Kiran.
“Ini!” kataku geram, mengacungkan sketsa di depan hidungnya. “Pamer popularitas?!” Kurobek kertas itu jadi delapan. Semua kepala berpaling kepadaku. Aku berfokus pada mata cokelat terang Kiran. Dia berusaha menyembunyikan kekagetannya.
Kutaburkan serpihannya di atas meja. Aku pengin dia terpancing marah atau melakukan sesuatu yang merusak citranya. Dia kan bukan superman, bukan Mr. Perfect, dan jelas bukan Prince Charming!
Kiran berdiri, tampak prihatin. “Maaf, Tya,” katanya, lembut dan jernih di telinga. “Aku lancang menggambar kamu tanpa izin. Kalau itu yang bikin kamu marah, sori berat. Tapi at least, terima ini ya?”
Lebih demonstratif dari serbuanku, dia memisahkan Welcome to 11A dan mengembalikannya kepadaku. Ketika aku bergeming, diraihnya tanganku dan diletakkannya kertas itu di telapakku, lalu dibuatnya jemariku mengenggamnya. Untuk sesaat dia menahan pula tanganku dalam genggamannya. Hangat.
Tapi sekonyong-konyong aku seperti kena setrum listrik. Kutarik tanganku. Kini, semua mata mencelaku. Tanpa kata, mereka menudingku: Ini dia, si pencari gara-gara. Huh, dengan akting begitu sempurna, Kiran menarik simpati semua orang.
Rista menyeretku pergi. “Tya, kamu ini kenapa sih?”
“Aku benci dia!”
“Apa? Baru seminggu kamu di sini….”
“Aku benci cowok jaim abis! Pasti dia punya kelemahan. Dark side. Aku pengin buka kedoknya!”
Rista terperangah. “Dengan kata lain, kamu menuduh Kiran aktor penipu? Dan aku terlalu bodoh mau jadi sobatnya selama ini?”
Kalau ya, memang kenapa?
Tanpa kata, Rista menyingkirkan aku dari bangkunya. Ya ampun, naifnya dia!
Dua minggu berikutnya, kelas jadi seperti neraka. Aku duduk dengan Olan, the truest and purest trouble maker, dan dicuekin teman-teman lain. Hanya Kiran yang masih ramah, walaupun aku tetap galak kepadanya. Ini semua kan gara-garanya. Lalu, ketika aku sudah tak tahan lagi dan pengin pindah kelas, Rista mengembalikan tasku ke bangkunya.
“Ada apa ini?” tanyaku curiga. Udara kelas juga mendadak berubah pagi itu. Senyum dan lambaian ramah kembali kuterima. “Kalian sadar aku benar, kan?”
Rista mendelik, tapi tak berkata apa pun. Belakangan aku tahu dari kasak-kusuk kelas. Kepingan informasi dari sana-sini yang kugabungkan. Ternyata… Kiran telah memohon-mohon kepada mereka agar tidak ikut campur. Kiran menyatakan bahwa sikapku terhadapnya adalah masalah pribadinya. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan teman-teman lain. Jadi mereka harus kembali bersikap biasa kepadaku. Kiran harus berusaha keras membujuk, karena menurut mereka, “anak baru itu” sudah menghina kelas. Memangnya siapa Ayutya, menampik sambutan dari anggota kelas ini?!
I got the picture, an ugly picture of me!
Sementara Kiran semakin meluluhkan hatiku dengan sikapnya. Tak ada yang dibuat-buat. Oh, God! I love everything about him.
Oh, God! Aku tetap benci dia. Kenapa? Aku tak tahu. Rista memberiku daftar panjang kelemahan Kiran. Hanya beberapa yang masuk akal, sisanya mengada-ada. Tapi, bukankah itu yang kucari? Mengetahui dia tak sempurna mungkin bisa mengurangi kebencianku.
Dan inilah the top 4 weakness of Kiran Dananjaya:
Aku menarik napas berat. Kukembalikan daftar itu kepada Rista sambil menahan air mata. “Thanks, Ris. Tapi ini nggak mengubah apa-apa.” Seandainya aku bisa berterus terang bahwa aku juga mencintai Kiran. Dan kebencian ini juga membuatku merana. Baru kali ini, aku tidak memahami diriku sendiri.
Dan aku semakin bingung dengan perbuatanku yang gila dua minggu lalu. Aku sendirian di kelas, izin tidak ikut olah raga. Kulihat ponsel Kiran menyembul di saku tasnya. Secepat ide itu muncul, secepat itu pula aku langsung melaksanakannya. Kukirimkan sms itu dari ponsel Kiran. Ringtone ponsel Rista pun berbunyi. Aku terkekeh sengau. Terdengar aneh di telingaku sendiri. Nah Mr. Perfect, rasakan pembalasanku!
Tapi menunggu perubahan sikap Kiran dan Rista ternyata sangat menyiksa. Mereka begitu cool dan wajar. Apa yang terjadi? Tak mungkin sms itu mereka abaikan. Atau mereka begitu pintar bersandiwara?
Resah. Marah. Kangen. Khawatir. Dendam. Puas. Menyesal. Panas. Dingin. Akibatnya dua hari aku tidak masuk sekolah.
“Pasti gara-gara cowok!” Mata tajam Mama mengenai sasaran.
Tangisku pecah. Kuceritakan semua yang kurasakan dan kualami. “Aku benci dia, Ma! The great Kiran Dananjaya! Akan kubuat dia merana!”
Mama terbelalak. “Apa katamu?”
“Aku pengin dia menderita. Beraninya dia buat aku jatuh cinta sekaligus benci!”
“Bukan itu. Siapa nama panjangnya tadi?”
“Dananjaya. Kenapa Ma?”
“Da-nan-ja-ya.” Bibir Mama bergetar. Wajahnya pucat seketika.
“Ada apa, Ma? Mama kenal dia? Atau keluarganya?”
“Tya, jangan ke mana-mana. Mama mau telepon Nenek Ayunilam. Biar dia yang menjelaskannya padamu.” Mama keluar kamar, meninggalkanku terbengong-bengong.
Nenek Ayunilam? Neneknya Mama yang berusia 80-an tapi masih cantik dan awet muda itu? Kenapa dia? Nenek Ayunilam atau yang biasanya kusebut Nenek Ayu saja, bisanya cuma membuatku takut dengan dongeng tentang kutukan ratu-ratu zaman dulu.
Benar saja, sekali lagi, kisah Ratu Ayundara dan Kartaran tumpah dari bibir Nenek Ayu. Kisahnya tak pernah berubah. Tapi kini aku berperan di dalamnya. Pemeran utama pula. Dan kisah itu bukan cuma dongeng, tapi sejarah keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ayundara adalah leluhurku. Aku pewarisnya yang ketujuh. Dalam darahku mengalir kebencian dan dendam warisan terhadap pewaris Kartaran. Arus yang lebih kuat daripada logika, dan cinta sekalipun.
“Kamu ingat lukisan wanita kuno di rumah Nenek? Dialah Ayundara. Nenek sudah sering menyingkirkannya. Tapi entah bagaimana dia kembali dan kembali. Terakhir, Nenek mengirimkan lukisan itu kepada teman di Amsterdam. Tahu-tahu, lukisan itu kini terpajang di Griya Seni keluarga Dananjaya di kota ini. Dan dari semua kota besar di Indonesia, kalian memilih pindah kemari!”
“Kenapa nggak dihancurkan?”
Nenek Ayu menggeleng. “Tak ada yang berani. Khawatir mengundang bencana lebih besar.”
“Kalau masih hidup, Ayundara pasti malu dengan perbuatannya.”
“Oh ya! Dia bahkan tak punya muka memandang kita melalui lukisannya.”
“Maksud Nenek?”
“Kalau sempat, tengoklah Ayundara di Griya Seni. Kamu pasti bisa lihat, seorang ratu yang cantik dan berkuasa, tak mungkin dilukis sedang menyembunyikan wajah.”
Kesempatan itu pun tiba minggu lalu. Kami berkunjung ke Griya Seni. Dan kutemukan Kiran menatap lukisan itu penuh kerinduan. Seolah menunggu wanita itu menoleh dan memperlihatkan seluruh wajahnya. Menyebalkan! Itu musuh besarmu, tahu! Aku mencoba memberitahunya. Tapi dasar bego, dia sama sekali tak tanggap!
Ah, kalau Kiran terlalu telmi, sebaiknya aku melibatkan Rista. Mungkin dia bisa membantu aku, tepatnya kami, keluar dari kekusutan ini. Kuraih ponselku, jari-jariku lincah menghubungi nomornya.
Suaranya serak. “Tya, entah jam berapa di situ, tapi di sini masih jam tiga.”
Aku tak menggubrisnya. “Kiran pewaris ketujuh Kartaran.”
“Ya ampun! Dini hari begini bicara soal warisan?”
“Ris, jangan kemana-mana. Begitu terang tanah, aku ke rumahmu.”
“Oh? Wah, batal deh kencanku kalau begitu.”
“Kamu jadian sama Kiran?” Aku tersengat. Lama kutunggu kabar itu. Tapi aku tak pernah siap mendengarnya. Kusatukan mereka agar menjadi jalan bagiku untuk menyakiti Kiran. Jalan terbuka, mestinya aku senang. Tapi yang kurasakan sekarang, merana sampai ke dasar hati terdalam. Kiran jelas-jelas tahu sms itu palsu, tapi jalan juga dengan Rista. Kenapa? Tak mau menyakiti perasaannya? Bagaimana dengan perasaanku?!
“Tya?! Masih di situ?”
“Ya. Sori. Aku cuma kaget.”
“Aku yang kaget! Kok kamu tahu aku jadiannya sama Kiran?”
“Ceritanya panjang. Kamu akan tahu nanti. Tidurlah lagi.” Kumatikan ponsel. Kupejamkan mataku. K itu identik dengan Kutukan.
****
Part 3
Rista: Potret Diri
Urusan Ayutya-Kiran selalu bikin aku pusing. Keduanya saling menyukai. Itu sudah jelas. Tak perlu mak comblang untuk menyulut daya tarik di antara keduanya. Tak perlu berlangganan sms jodoh untuk mengetahui mereka saling cocok. Tapi sikap Tya terhadap Kiran begitu aneh. Dan Kiran malah membuat gerakan sembrono dengan nge-date aku. Walau setelah kami jadian, tak ada perubahan apa pun dalam sikapnya dan rutinitas kami. Sahabatan atau pacaran dengan Kiran, sama saja. Yang tahu pun hanya kami berdua.
Tapi ternyata Tya tahu! Dan kalau mengingat isi sms itu, mengingat lagi ekspresi terkejut Kiran, sikapnya… Ah, kupikir aku tahu apa yang terjadi. Dan dalangnya akan datang beberapa jam lagi. Belum pernah aku selega ini sejak pacaran dengan Kiran. Seminggu saja sudah cukup.
Jam 7, Tya datang dengan wajah kusut. “Aku minta maaf. Kamu jadian dengan Kiran setelah sms itu, kan? Tapi Kiran nggak ngirim. Aku yang ngirim.” Dia memuntahkan kata-katanya secepat ledakan popcorn di panci yang terlalu panas.
“Aku tahu.”
“Apa? Kamu tahu, Kiran tahu, tapi kalian jadian juga?” Kecemburuannya begitu nyata.
“Nggak begitu. Baru kusimpulkan waktu kamu telepon tadi. Dan Kiran, God bless his heart, dia mau jadian sama aku pasti cuma karena nggak mau menyakiti aku.”
“Sori, Ris.”
“Nggak apa-apa. Tapi kamu berhutang penjelasan lengkap.”
“Ya. Aku mau cerita semua, meski nggak yakin ini masuk akal.”
“Try me.”
Ayutya bimbang sejenak, lalu memulai dengan lukisan Ayundara di Griya Seni. Wanita itu leluhurnya. Karena patah hati ditolak Kartaran, Ayundara mengeluarkan kutukan yang membuat sengsara keturunan kedua pihak. Setelah Nenek Ayunilam, Ayutya adalah pewaris ketujuh. Dan Kiran pewaris Kartaran ketujuh. Kutukan itu membuat Ayutya membenci dan bertekad menyakiti Kiran dengan segala cara. Padahal, sejak pertama kali bertemu Kiran, dia jatuh cinta.
Tya menangis. Belum pernah kulihat dia selemah itu.
“Setelah Nenek Ayu, kenapa kamu? Bukan nenekmu atau ibumu?”
“Kata Nenek Ayu, pewaris Ayundara hanyalah yang cantik dan ambisius. Dan kupikir, nama juga berperan di sini. Ayundara, Ayularas, Ayusari dan entah Ayu-siapa lagi, lalu Ayunilam atau Nenek Ayu, dan aku Ayutya. Mamaku dan ibunya tak punya nama begitu. Soal ambisius, Nenek Ayu itu perintis bisnis keluarga, yang kelak akan diwariskan kepadaku.”
“Sedangkan pewaris Kartaran,” lanjut Tya. “Mungkin lelaki yang berbakat melukis, dan namanya diawali huruf K. Korban Nenek Ayu adalah kakek buyut Kiran, pelukis Karyadi Dananjaya. Selain dia dan Kiran, aku nggak tahu pewaris lainnya.”
“Pastinya bukan Om Giri, apalagi Om Gunawan, papi Kiran,” kataku, berpikir keras. Legenda Ayundara tidak populer dalam keluarga Kiran. Mereka mungkin tidak tahu-menahu atau bahkan tidak percaya dengan kutukan itu. Padahal, pihak yang dikutuklah yang mestinya menangkal kutukan. Karena tak ada usaha di pihak mereka, tak heran kutukan itu berlanjut dari masa ke masa. “Tya, kita harus memberitahu Kiran. Dialah yang harus memusnahkan kutukan itu.”
Dan tanpa menunggu persetujuan Tya, aku menelepon Kiran. Tidak dijawab, tapi tirai di seberang sana tersingkap, sepasang tangan menggeser jendela ke atas, lalu kepala Kiran menyembul.
“Sori kesiangan!” serunya, menguap. Lalu terbelalak, menyadari ada Tya di sampingku. Buru-buru ditariknya kepalanya sampai terbentur bingkai jendela. Ouch!
Kulihat sunggingan geli di bibir Tya dan sorot matanya yang penuh cinta. Tapi hanya sesaat. Ekspresinya mengeras, “Bego!” makinya.
Aku memandang Tya, ngeri. Ada dua orang berbeda dalam dirinya.
Teleponku berbunyi. Kiran. Kusuruh dia datang segera. “Aku mandi dulu ya,” sahutnya gugup.
Sembari menunggu, Tya berubah-ubah cepat. Sebentar memandang rindu ke arah kamar di seberang, sebentar membara oleh kebencian Ayundara. Usahaku untuk mencairkan ketegangannya sia-sia saja.
Kiran muncul tak lama kemudian. Kupikir kehadiran Tya akan membuatnya memilih jalan yang lebih beradab, yaitu melangkah melalui pintu depan. Tapi Kiran tetap Kiran. Dia melompat keluar dari jendelanya, memanjat pagar pembatas antarhalaman kami, dan duduk di teras paviliunku. Kami menemuinya di sana.
“Hai, Tya,” sapanya. Wangi sabun dan sampo menguar segar dari tubuhnya. Dia memakai T-shirt biru dengan lukisan abstrak di dada dan celana panjang khaki. Rambutnya setengah basah membalut elok kepalanya. Sedikit acak-acakan karena melompat-lompat tadi. Bahkan aku yang tidak punya perasaan lain terhadapnya kecuali rasa sayang terhadap sahabat, sekali-sekali terkesima memandangnya. Tuhan benar-benar pemurah memberikan segala keindahan pada makhluk-Nya yang satu ini.
Ayutya cuma mendengus. Dia menjaga jarak agak jauh. Tapi wajahnya yang keruh dan sikap tubuhnya yang bagai harimau terluka seolah ingin menerkam Kiran. Aku menghela napas. Jelas, akulah yang harus bercerita. Kucoba meringkas tanpa mengurangi keseriusan masalah.
“Jadi, Kiran, kamulah yang harus mengakhiri kutukan itu,” simpulku.
Kiran memandang Tya, dengan binar seperti baru pertama kali melihatnya. Lalu memandangku, seperti menyadari sebuah kesalahan dan hendak meminta maaf. Aku mengangguk, seratus persen mengerti dia hendak meralat hubungan kami. Kiran tersenyum.
“Tya, maaf, waktu itu aku nggak menganggap serius ceritamu,” katanya. “Rista benar, itu karena kami nggak tahu apa-apa soal kutukan Ayundara. Tapi kalau memang antikutukan itu ada di keluarga Dananjaya, maka kita harus mencarinya di Griya Seni. Ayo!”
Diantarkan supir Kiran, kami pergi ke sana. Sepanjang perjalanan, Tya duduk mengerut di kursi belakang bersamaku. Luar biasa upayanya menahan diri agar tidak bergerak-gerak gelisah. Dia tampak menggigil sekaligus berkeringat kegerahan. Matanya terpaku pada bagian belakang kepala Kiran yang duduk di samping supir. Dia seperti orang asing. Aku bergidik diam-diam.
Kami masuk dari pintu belakang, dan langsung ke galeri keluarga. Kiran mencoba membuka setiap lemari dan laci. Semuanya terkunci. “Semua dokumen dan buku catatan lama ada di sini. Tapi, Om Giri pegang kuncinya.” Kiran lalu menelepon.
Aku dan Tya berkeliling mengamati lukisan dan foto kuno yang dipajang secara kronologis.
“Ini Karyadi Dananjaya.” Tya menunjuk lukisan pria yang begitu mirip Kiran. Sang pewaris keenam.
Lalu kutemukan dua lagi lukisan potret diri orang-orang bernama awal huruf K. Kusnadi dan Kardiman. “Tak ada lukisan pewaris dari generasi sebelum mereka.”
“Semoga yang tiga ini sudah bisa memberi kita petunjuk,” kata Kiran. Dia mengambil tangga aluminum dan memasangnya di bawah lukisan. Lalu dia naik turun untuk mengambil ketiga lukisan itu dan meletakkannya berjajar di meja besar. Kami mengamati mereka tanpa tahu apa yang harus dicari.
Mata seniman Kiran menemukannya lebih dulu. Dia mengambil kaca pembesar. “Lihat destar mereka. Ada pola-pola seperti tulisan kuno di sana.”
Kami bergantian mengintip melalui kaca pembesar.
Kiran menggosok-gosok dagunya, berpikir. “Hiasan destar mereka serupa benar. Ini aneh, karena masa hidup ketiganya terpisah lama sekali. Pasti dilukiskan belakangan oleh para Mr. K berikutnya. Mungkin semacam pesan atau kode rahasia. Akan kutanyakan kepada Om Giri.”
Om Giri menjawab melalui speakerphone. “Kiran, kamu selalu penuh kejutan. Kenapa kamu tertarik….”
“Jadi ada artinya kan?” Kiran menukas.
“Om sudah lama menelitinya. Papimu bilang….”
“Apa artinya, Om?” Kami serempak mendesak.
“Oh boy! Siapa saja di situ? Apa yang sedang kalian lakukan di sana?” Nada suara Om Giri menjadi sangat khawatir. Sekelompok remaja di galerinya tercinta. Bisa berarti apa saja.
“Cuma Rista dan Tya,” sahutku ceria. “Ceritanya belakangan ya, Om. Tolong, katakan apa artinya?”
Om Giri mendesah tak berdaya. “Artinya: Dia meminta pengganti diriku yang tak sanggup kukabulkan pula. Penelitianku belum selesai, jadi….”
Kiran memutuskan hubungan. Dia menggumamkan kalimat yang kucatat di sehelai kertas itu. Dia meminta pengganti diriku yang tak sanggup kukabulkan pula.
“Yang minta pasti Ayundara. Mr. K tidak mampu mengabulkannya pula. Apa yang diminta Ayundara sebelumnya?” tanyaku.
“Cinta,” sahut Tya pelan. “Yang gagal diperoleh Ayundara. Lalu dia minta pengganti diri Mr. K. Tapi itu juga tidak diperolehnya.”
“Kali ini Mr. K tak sanggup mengabulkan. Bukan tak mau,” sanggah Kiran.
Tya membelalak kesal. “Begitukah?” semburnya sinis.
Kiran tercengang memandang Tya, lalu buru-buru menekuni lagi lukisan leluhurnya.
“Hei, ketiganya pelukis hebat kan?” kucoba mencairkan suasana.
“Ya. Yang terhebat di generasinya,” jawab Kiran.
“Tapi lukisan-lukisan ini bukan karya mereka sendiri. Lihat, pelukisnya semua orang lain,” kataku menunjuk tanda tangan di bagian bawah setiap kanvas.
“Ris, itu nggak aneh. Pelukis hebat zaman sekarang pun banyak yang nggak bisa membuat potret diri. Apalagi zaman Kartaran, waktu cermin belum lagi ditemukan. Om Giri saja….” Tiba-tiba Kiran tertegun. Lalu menepuk tanganku bersemangat. “Ris, kamu jenius!”
“Apa?”
“Potret diri. Itulah yang diminta Ayundara. Dulu Kartaran tidak bisa mengabulkan permintaannya karena tak sanggup membuat potret diri sendiri. Kutukan itu berlanjut karena keturunannya, para Mr. K ini, juga tidak bisa membuat potret diri mereka sendiri.”
“Potret diri? Benarkah itu antikutukannya?” bisik Tya, harap-harap cemas.
“Entahlah. Kita coba saja.” Kiran tampak bersemangat. “Ayo, ke bengkel.”
“Oh, Mr. K ketujuh mau bikin potret diri!” Tya lagi, semakin kasar dan histeris.
Aku merapat pada Kiran. “Kuharap kamu benar-benar bisa melukis. Tya makin gawat.”
Kiran bekerja tanpa kata, menyiapkan kuda-kuda, kanvas berukuran 60 x 80 sentimeter persegi, dan palet cat di depan cermin besar, lalu mulai menyapukan kuasnya sambil sekali-sekali memandang bayangan cerminnya. Tya mengawasi dengan wajah memerah. Aku berdiri dekat pintu, jauh darinya.
Satu jam yang terasa selamanya. Akhirnya Kiran meletakkan palet.
Tya mendekat. “Hmm,” gumamnya. Tiba-tiba disambarnya palet itu untuk dilemparkan ke arah potret diri Kiran. Kiran yang waspada melindungi lukisan dengan tubuhnya. Cat aneka warna tumpah menodai punggungnya.
“Rista, bawa lukisanku ke Ayundara. Cepat.”
Aku terkesima, tak mampu mencerna perintah itu. Kiran bergulat mencegah Tya merusak lukisannya.
“Rista, CEPAT PERGI!”
Kusambar kanvas itu dari tangan Kiran dan kubawa lari ke ruang Ayundara. Di belakangku Tya mencoba merangsek. Kiran menahannya. Aku sampai di sana dengan selamat, tapi aku tak bisa memasang lukisan Kiran di samping Ayundara. Akhirnya, kuacungkan kanvas itu, menghadapkan Kiran kepadanya. Dan aku menunggu. Waktu seakan terhenti.
Bunyi sepatu Tya dan Kiran bergema di lorong. Tya memaki, mengancam, dan Kiran menenangkannya. Lalu ada yang menjerit keras. Terkejut, aku menoleh ke pintu. Kiran memegangi Tya di sana. Tapi kusadari, bukan Tya yang menjerit tadi. Terdengar begitu dekat di kepalaku. Aku kembali menghadap Ayundara.
Wanita itu kini menghadapku dengan sepenuh wajahnya. Aku bisa melihat jelas matanya yang angkuh, senyumnya yang sinis, dagunya terangkat.
Bibirku bergetar, tak mampu berucap. Aku limbung. Kanvas terasa lebih berat. Kiran sigap menangkapku. Tya memelukku. Air matanya bercucuran, tapi dia tersenyum bahagia. “Ris, kami sudah bebas. Aku sudah bebas. Terima kasih.”
“Di sini rupanya kalian!” Om Giri muncul. “Kiran, ada apa ini? Kenapa punggungmu penuh cat begitu?”
Kiran malah melonjak-lonjak seperti balita. “Om, lihat! Ayundara berbalik ke depan!”
“Kamu ngomong apa sih?” Om Giri memeriksa Ayundara, curiga.
“Aku berhasil mematahkan kutukannya. Dia nggak perlu lagi menyembunyikan muka.”
Om Giri menatapnya ganjil. “Kiran, aku nggak ngerti maksudmu. Tapi, Ayundara masih sama seperti yang kutinggalkan kemarin, cantik dan anggun.” Om Giri geli sendiri, lalu beralih pada potret diri Kiran di lantai. Siulan kagum terlepas dari bibirnya ketika dia berjongkok memungutnya. “Apa kubilang, kamu berbakat melebihi kakek Karyadi!”
Kami memandang Ayundara, tak yakin lagi apa yang berubah pada lukisannya. Lalu kami saling pandang. Kiran tampak hendak berkeras tentang perubahan pose wajah Ayundara, tapi urung melihat senyum lembut Ayutya. Kutukan dan antikutukan sudah tak penting lagi. Aku tertawa puas bareng Om Giri. []
(Dimuat di Majalah STORY TEENLIT MAGAZINE, sekitar September 2010… lupa dicatat)
Banyak di antara kita “beruntung”, menjadi penulis yang membaca, pembaca yang menulis, dan sudah merasakan keajaiban di kedua sisi. Namun demikian, itu tidak memudahkan penulis menerima dan memahami reaksi negatif pembaca terhadap bukunya. Penulis cenderung defensif dan lupa bahwa sebagai pembaca, kita juga bersikap kurang lebih sama. Yaitu punya standard penilaian sendiri yang berpangkal pada fakta bahwa:
Itu gambaran umum tentang pembaca. Lebih detailnya, ada beberapa jenis pembaca, yang tentunya perlu direspons berbeda oleh penulis:
Pembaca “Friendly” (=temannya penulis ^_^)
Ia tertalu sopan untuk mengkritik tulisan teman. Mencari-cari hal positif untuk dipuji secara terbuka di medsos dan menyembunyikan kerutan kening dan kekecewaan. Apalagi kalau bukunya dikasih gratis oleh penulisnya sendiri. Apalagi kalau si pembaca ini juga sesama penulis, yang tahu susah payahnya menulis, dan yang berharap mendapatkan perhatian balik ketika bukunya sendiri terbit nanti.
Sebagai penulis, kita perlu masukan positif dari siapa saja, share dan likes di medsos membantu meningkatkan kepercayaan diri. Tetapi jangan terlena. Jangan berpuas diri dengan readership ini semata. Kemampuan kita belum teruji kalau hanya mengandalkan pembaca dari kalangan sendiri.
Pembaca Umum (It’s a jungle out there)
Buku Anda akan dimutilasi, dicacah, dicincang, down to each word. Satu dua pujian bisa saja mampir, tapi bersiaplah dengan seribu celaan. Dari masalah typo yang tidak penting banget, sampai masalah yang mungkin timbul akibat kesalahapahaman pembaca sendiri. “Ini novel jelek banget. Fantasi kok begini.” Padahal buku Anda adalah novel realistik psikologis. Beruntung kalau kita menemukan kritik salah paham ini dan bisa meluruskan, sering kita tahunya setelah sekian lama. Setelah buku itu punah dari pasaran.
Atau, “Kapok dah baca, merusak hari saya! Gak rekomended deh. Rugi…bla bla bla….” Padahal cuma masalah selera yang diiakui pembaca di baris terakhir review-nya. Hehehe.
Menyebalkan memang, tapi ingat 6 aturan utama di atas. Pembaca berhak berpendapat. Kata-katanya penting. So, jadikan saja sebagai bahan introspeksi. Kalau hanya satu dari sekian banyak pembaca yang salah paham, mungkin bisa diabaikan. Tapi kalau banyak dan berulang, perlu kita evaluasi tulisan kita sendiri, kok bisa membuat orang salah paham. Mungkin kita yang salah menyampaikan. Maksud tak sampai karena keterbatasan kita dalam teknik menulis. Perbaiki saja. Tak perlu merasa down, ngambek, “mutung”, tak mau menulis lagi. Atau yang lebih membuang waktu, membuat status defensif dengan mencela pembaca ybs, mengatainya sok tahu, sok pintar, tidak sopan, dan berlanjut dengan ratapan tentang sulitnya menulis, betapa orang tidak menghargai…bla bla….
Stop. Kuatkan mental. Berpikir positif. Ada kritik berarti ada pembaca. At least. Dan dari onggokan abu itu muncullah Phoenix baru yang lebih cantik….. cieee bahasanya!
Kalau Anda mau tahu kejamnya hutan rimba, tengoklah Goodreads. Bacalah review-review 1-2 bintang yang ditulis oleh pembaca umum yang bukan penulis/editor/penerjemah. Bahkan penulis besar dan sukses di dunia dapat bagian review pahit juga.
Tapi di komunitas pembaca seperti itulah, Anda bisa mendapatkan penilaian sebenarnya. Karya Anda teruji di sana. Pembaca yang kritis, pembaca yang santun dan objektif, pembaca yang jeli, juga banyak di sana. Mereka adalah sekutu Anda untuk meningkatkan kualitas karya.
Pembaca Kritis, Objektif, dan Santun
Kita beruntung kalau mendapatkan readership seperti ini. Apalagi pembaca yang paham benar menganalisis karya, berpengalaman dan jeli melihat kelemahan dan kelebihan. Dengarkan kata-kata mereka. Pertimbangkan saran-saran mereka untuk perbaikan pada karya selanjutnya.
Sebagai pembaca, ehem, aku memilih menjadi yang seperti ini. Tentu saja aku membaca berdasarkan pertimbangan selera, mood, waktu, dan faktor-faktor lainnya juga. Tetapi kalau diminta secara profesional mereview, aku lebih suka menyampaikan kritik dan pujian secara pribadi.
Pembaca Orangtua
Sebetulnya mereka lebih menjadi orangtua daripada pembaca. Memilah-milah dan membeli buku untuk anak mereka. Dari sekadar skimming hingga mencermati tiap gambar dan kata. Sensornya peka luar biasa. Apalagi bagi orangtua yang tujuannya menjadikan buku sebagai mitra pendidik. (Wow, suatu kehormatan bukan? Banyak penulis bacaan anak dengan senang hati berusaha memenuhi standar itu. Tapi banyak juga yang sedikit “nakal”, ingin mencuri hati anak dan menghiburnya saja, jadi tidak peduli dengan pesan moral yang dituntut orangtua untuk dieksplisitkan… hehehe, kayak aku)
Untuk penulis yang anti mainstream, ada risiko buku Anda disebut “tidak bermoral” eh, dipertanyakan, “Mana atau apa pesan moralnya?”….
Wajar…. Literasi anak memang dipenuhi standar berbeda-beda. Yakini apa yang kita yakini. Terima masukan. Pertimbangkan. Belajar lagi. Yakini apa yang kita yakini. Proses lagi. Di dalamnya tentu ada usaha menyampaikan apa yang kita yakini dengan ilmu dan kesantunan. Dan mungkin dalam prosesnya, Anda akan menemukan formulasi yang tepat untuk merangkul orangtua sekaligus anak-anak mereka.
Pembaca Anak
Di satu sisi ada benarnya orangtua berdiri di antara anak dan buku dengan tameng terangkat. Aku juga melakukan itu, hanya tamengnya bolong-bolong dan miring-miring. Hahaha. Karena aku percaya anak-anak. Karena aku pernah menjadi anak-anak. Karena aku penulis bermoral. Dan karena buku–meskipun dapat memberikan kesan mendalam–risikonya tidak sedahsyat visualisasi orang dewasa yang dijejalkan kepada anak melalui film/animasi. Buku, untuk sampai pada kesan dahsyat perlu pengalaman dan kecanggihan pembaca dalam menginterpretasi dan berimajinasi. Dengan kata lain: satu kalimat yang dianggap mengerikan oleh orangtua belum tentu menghasilkan visualisasi yang sama dalam benak anak. Itu bergantung pengalamannya, juga bergantung konteksnya. Buku lebih aman bagi anak ketimbang video. Dan literasi visual anak menjadi hal penting untuk diperhatikan.
Di sisi lain, pembaca anak adalah yang paling jujur. Meskipun orangtua, penulis, penerbit, berbusa-busa mempromosikan sebuah buku, mereka punya mekanisme seleksi sendiri yang kadang susah dipahami orang dewasa. Di hadapan anak, penulis itu sama, tak peduli apakah pernah menang lomba, menyabet aneka award, atau baru muncul kemarin sore (lha kan jelas, yang memenangkan penulis adalah juri dewasa, jadi kriterianya juga beda). Kadang satu gambar kecil di cover membuat anak-anak jatuh cinta dan tak mau lepas dari buku tersebut. Kadang warna berperan. Kadang karakter yang mewakili dirinya menjadi faktor penentu. Bisa jadi yang disukai anak sebetulnya adalah suara Ayah/Ibunya ketika membacakan satu buku. As simple as that. Anak lalu mengasosiasikan kebahagiaannya saat itu dengan buku yang dipegang. Maka, dimintanyalah dibacakan sampai tujuh kali dalam semalam.
Bukan berarti aku menafikan peran penulis dan ilustrator. Buku bagus selalu stands out of the crowd. Tapi pada buku anak, penulis jangan ge-er banyak-banyak dulu deh ketika bukunya disukai anak sampai kucel. Banyak faktor penyebabnya. Ge-er berlebihan bikin lengah. Jika anak sudah lebih besar, dapat mencerna buku secara mandiri, dapat menyampaikan hal-hal yang disukai atau tidak disukainya, dan cenderung memilih buku berdasarkan nama penulis, bolehlah kita salto. Selamat untuk kita 🙂 Justru inilah penghargaan terbesar bagi seorang penulis bacaan anak.
Salam kreatif…..
Catatan Definisi